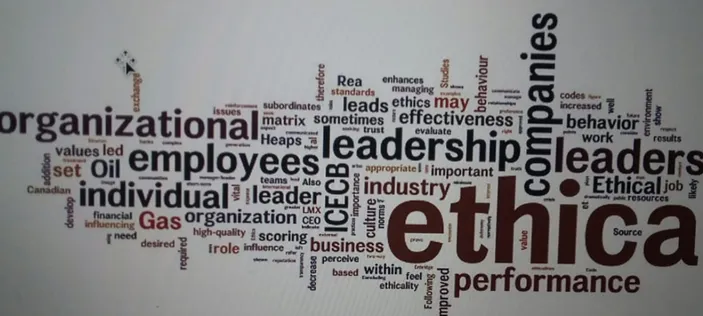Mencermati tantangan-tantangan global yang sangat bervariasi di berbagai konteks. Sebagaimana Peter Fisk (2022) – seorang Business Catalyst dan Keynote speaker dalam “Megatrends 2020-2030 Keynote and Workshop” menyebutkan ….. konflik-konflik baru dengan konsekuensi secara ekonomi, politik dan logistik, kemudian kenaikan inflasi, harga minyak, dan pertumbuhan yang stagnan semakin menantang norma-norma yang sedang berlaku. Demikian pula, pertumbuhan sedang mengalami pergeseran, inovasi tiada henti, disrupsi semakin cepat, ekspektasi tinggi, dan ketegangan sosial meningkat.
Memahami dan memanfaatkan kekuatan perubahan yang dramatis ini akan membantu membuat pilihan strategis yang lebih baik, membentuk pasar yang menguntungkan, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah, jelasnya. Bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi masa depan – baik sebagai tantangan maupun peluang – dalam strategi dan inovasi merangkul kekuatan perubahan yang paling signifikan? Apakah teknologi membentuk segalanya?, tapi yang penting adalah dampaknya. Artinya, Tren akan memandu pilihan untuk masa depan, termasuk bagi perguruan tinggi (PT).
Megatren, Problematika Kualitas PTS vs Permendikbudristek No. 53/2023
Analisis McKinsey baru-baru ini menunjukkan bahwa gelombang perubahan yang cepat, yang diciptakan oleh tren industri dan geografis adalah kontributor paling penting. William Gibson, penulis fiksi ilmiah memperingatkan, “Masa depan sudah ada di sini, hanya saja belum merata”. Oleh karena itu, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana menggunakan “megatren” untuk membantu memahami kemungkinan-kemungkinan yang ada, dan kemudian bagaimana dapat membentuk masa depan, sesuai dengan keinginan?
Bila demikian, apa yang dimaksud “megatren”? Megatren adalah perubahan besar dalam bidang sosial, ekonomi, politik, lingkungan hidup, atau teknologi yang terjadi secara perlahan, namun jika terjadi dapat mempengaruhi berbagai aktivitas, proses, dan persepsi, mungkin selama beberapa dekade. Hal-hal tersebut merupakan kekuatan mendasar yang mendorong perubahan di pasar global dan kehidupan kita sehari-hari. Megatren juga merupakan penanda yang berharga, berwawasan luas, dan penting bagi masa depan.
Megatren tentunya memiliki dampak pula pada cara perguruan tinggi beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun global. Perguruan tinggi yang responsif dan fleksibel dalam mengatasi tantangan ini memiliki potensi menjadi pemimpin dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Disinilah transformasi pendidikan tinggi sangat diperlukan.
Di tengah tantangan global di atas yang dikenal “megatrend”, kita dihadapkan pada realita sebagian besar perguruan tinggi swasta (PTS) kita masih bergulat dalam meningkatkan mutu dan menjadi institusi yang sehat. Terdapat lebih dari 2.984 PTS, dengan 8,2 juta mahasiswa, tetapi 50-60 persennya kurang sehat dan harus segera disehatkan, jelas Prof. Dr. Thomas Suyatno, Ketua Umum ABP PTSI. Sedang, Ketua Umum Asosiasi PTS Indonesia (APTISI), Prof. Dr. Budi Djatmiko mengatakan, penjaminan mutu PT harus menjadi komitmen pimpinan dan penyelenggara PT. Kondisi saat ini diperkirakan ada 1.500 PTS belum terakreditasi institusi dengan berbagai permasalahan.
Rektor Universitas YARSI Jakarta, Prof. Dr. Fasli Jalal menjelaskan ”kita menyepakati mutu dengan menyepakati aturan main sehingga perlakuan pemerintah harus sama antara PTS dan PTN. Biaya operasional untuk mahasiswa bisa menjamin mutu dasar, yang sebenarnya bisa dilaksanakan PTS juga”. Sementara Ketua Konsorsium PTS Indonesia Maskuri menyoroti pembiayaan LAM menjadi beban PTS. Padahal, akreditasi selama ini dibiayai pemerintah sebagai wujud komitmen pada penjaminan mutu.
Nampak, sebagian PTS kesulitan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan lembaga. Para pengelola PTS merasa kurang mendapat dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah. Padahal, keberadaan institusi pendidikan tinggi swasta turut menentukan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah sangat dinantikan.
Baru-baru ini pemerintah menerbitkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengafirmasi percepatan transformasi pendidikan tinggi. Permendikbudristek ini merupakan angin segar yang diharapkan memberikan energi baru dalam meningkatkan mutu dan kesehatan institusi pendidikan tinggi. Permendikbudristek tersebut didalamnya mengandung aspek otonomi akademik, serta akuntabilitas dan transparansi bagi perguruan tinggi, yang tampaknya merupakan kebijakan yang diharapkan untuk menjawab tantangan tersebut di atas. Walau tentunya dibutuhkan kecerdasan perguruan tinggi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang mereka usung dalam menjalankan Tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) sebagai pengejawantahan fungsi perguruan tinggi.
Mengapa Otonomi Akademik ?
Otonomi akademik perguruan tinggi merupakan prinsip dasar dalam dunia pendidikan tinggi yang memberikan perguruan tinggi kebebasan untuk mengelola dan mengatur aktivitas akademiknya tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak pemerintah atau eksternal. Dalam mengimplementasikan otonomi akademik, tentu saja pendidikan tinggi memiliki potensi untuk memberikan dampak paling signifikan dalam membangun SDM unggul. Oleh karena itu, perlu adanya upaya percepatan adaptasi pendidikan tinggi di Indonesia agar dapat bersaing secara global.
Otonomi akademik perlu dan penting bagi perguruan tinggi? Sangat benar, mengingat beberapa hal yang menjadikan alasan.
- Mendorong Inovasi dan Penelitian. Otonomi akademik memungkinkan perguruan tinggi mengembangkan kurikulum, program, dan kebijakan mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka merespons dengan cepat perkembangan ilmiah dan teknologi terbaru, serta mengeksplorasi berbagai pendekatan baru dalam pengajaran dan penelitian.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan. Otonomi akademik memungkinkan staf pengajar dan pengelola perguruan tinggi membuat keputusan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan. Mereka dapat mengatur standar akademik, merancang kurikulum yang relevan, dan menilai kualitas program pendidikan mereka tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan.
- Kebebasan Berpendapat. Otonomi akademik memberikan dosen dan peneliti kebebasan menyampaikan pandangan dan penelitian mereka tanpa takut tekanan atau hambatan eksternal. Ini penting dalam mendukung pengembangan pengetahuan dan pemikiran kritis.
- Pembangunan Karakter dan Nilai. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab membentuk karakter dan nilai-nilai etika mahasiswa. Otonomi akademik memungkinkan perguruan tinggi merancang program pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai etika dan kultural yang mereka anut.
- Menyediakan Layanan yang Lebih Relevan. Otonomi akademik memungkinkan perguruan tinggi merespons kebutuhan masyarakat dan pasar tenaga kerja setempat. Mereka dapat merancang program pendidikan yang lebih relevan dan responsif terhadap permintaan dan tantangan yang ada.
- Kebebasan Akademik. Otonomi akademik melindungi kebebasan akademik, yang mencakup hak dosen mengajar dan melakukan penelitian tanpa takut represi atau intervensi. Ini merupakan aspek penting dalam mempromosikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir.
Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menyesuaikan sistem penjaminan mutu mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi, tanpa diatur detail dan kaku oleh pemerintah.
Mengapa Akuntabilitas dan Transparansi?
Otonomi akademik adalah prinsip penting dalam sistem pendidikan tinggi karena memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi berkembang dan berinovasi, sesuai dengan misi dan visi mereka. Otonomi akademik yang seimbang membantu menciptakan lingkungan di mana perguruan tinggi dapat berkembang, berinovasi, dan memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi.
Meskipun otonomi akademik penting, namun harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi perlu memenuhi standar kualitas tertentu dan melaporkan kinerja mereka kepada pihak berwenang dan masyarakat. Akuntabilitas menciptakan kerangka kerja untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perguruan tinggi, serta memastikan bahwa sumber daya dihabiskan dengan efisien dan efektif. Hal ini melibatkan pengembangan standar, penilaian, dan pengukuran kinerja yang jelas, baik untuk program akademik maupun manajemen keuangan. Akuntabilitas membantu memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi tanggung jawab mereka terhadap mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah yang mungkin mendanainya.
Sedangkan, Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Perguruan tinggi yang transparan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dana, dan pelaporan kinerja memberikan pemangku kepentingan (seperti mahasiswa, staf, orang tua, dan masyarakat) informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan. Transparansi juga dapat mengidentifikasi masalah atau ketidakpatuhan yang perlu diperbaiki.
Dalam rangka menjalankan otonomi akademik dengan baik, perguruan tinggi perlu mencapai keseimbangan antara kreativitas akademik dan tanggung jawab sosial. Akuntabilitas dan transparansi adalah alat penting untuk mencapai keseimbangan tersebut dan memastikan bahwa perguruan tinggi berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan.
Menjalankan akuntabilitas dan transparansi, maka perguruan tinggi memiliki aspek- aspek penting berikut.
1) Memastikan Kualitas Pendidikan. Akuntabilitas dan transparansi membantu memastikan bahwa perguruan tinggi tetap memberikan pendidikan berkualitas. Dengan menerapkan standar dan proses evaluasi yang transparan, baik pihak internal maupun eksternal dapat memantau dan memastikan bahwa program akademik dan kegiatan riset berada pada tingkat yang memadai.
2) Pemenuhan Harapan Publik. Perguruan tinggi adalah lembaga yang dibiayai oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, ada harapan bahwa perguruan tinggi akan menggunakan dana publik dengan efisien dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi membantu memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan manfaat publik.
3) Keberlanjutan Keuangan. Perguruan tinggi perlu menjalankan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Ini mencakup penggunaan dana, alokasi sumber daya, dan pelaporan yang jelas tentang keuangan mereka. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat menjaga keberlanjutan keuangan mereka dan menghindari masalah keuangan yang dapat merugikan mahasiswa, orang tua, dan staf( dosen dan pegawai).
4) Pemberian Informasi yang Jelas. Transparansi dalam informasi mengenai program akademik, biaya, dan kebijakan perguruan tinggi membantu mahasiswa, calon mahasiswa, dan orang tua dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pendidikan mereka. Informasi yang jelas dan mudah diakses membantu menjaga kepercayaan dalam sistem pendidikan tinggi.
5) Pertanggungjawaban Internal. Akuntabilitas dan transparansi juga diperlukan untuk pertanggungjawaban internal. Hal ini membantu perguruan tinggi mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka, memastikan bahwa tujuan dan nilai mereka diwujudkan, serta mengatasi masalah dan kekurangan yang mungkin timbul.
6) Keberlanjutan Reputasi. Reputasi perguruan tinggi sangat penting dalam menarik mahasiswa, dosen, dan sumber daya eksternal. Akuntabilitas dan transparansi membantu menjaga reputasi yang baik dengan memastikan bahwa perguruan tinggi menjalankan praktik yang etis dan berkelanjutan.
Keseimbangan antara ketiga elemen di atas diharapkan membantu menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang dinamis, efektif, dan dapat dipercaya. Semoga.